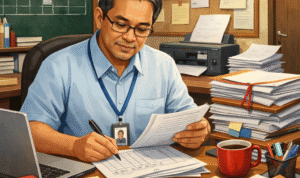OPINI: Muh. Ikbal (Dosen Fakultas Bahasa dan Sastra UNM)
Banjir besar yang melanda beberapa wilayah di Sumatra dan Aceh beberapa hari terakhir bukan hanya menyisakan kerusakan fisik. Air bah itu juga menyeret kita pada persoalan lain yang tidak kalah rumit yaitu penjarahan terhadap minimarket dan gudang Bulog. Dalam pemberitaan terbaru, sejumlah outlet ritel di Kota Lhokseumawe, Aceh Tamiang, dan Langkat dilaporkan dibobol warga yang nekat mengambil sembako. Salah satu laporan media menuliskan bahwa gudang penyimpanan Bulog ikut menjadi sasaran sehingga ratusan kilogram beras dan bahan pangan lain hilang. Di tengah situasi darurat yang semestinya memperkuat empati dan gotong royong, tindakan penjarahan itu menimbulkan pertanyaan lebih dalam tentang bagaimana bahasa media mengonstruksi kejadian tersebut dan bagaimana wacana publik membentuk cara kita menilai tindakan yang terjadi saat bencana.
Dalam analisis wacana kritis, setiap kata dalam pemberitaan tidak hanya memberi informasi tetapi juga membawa ideologi. Media nasional dan lokal menggunakan istilah penjarahan untuk menggambarkan tindakan warga yang mengambil barang dari minimarket dan gudang pangan. Kata penjarahan memberi beban makna kriminal sekaligus moral. Ia menempatkan warga sebagai pihak yang salah dan minimarket sebagai pihak yang dirugikan. Namun pemilihan kata itu sering mengabaikan konteks bahwa warga telah berhari hari kelaparan, akses logistik tertutup, dan bantuan resmi belum menjangkau sebagian wilayah. Di beberapa video amatir yang beredar, warga mengatakan bahwa anak anak mereka tidak makan seharian dan tidak tahu kapan bantuan datang. Bahasa penjarahan dalam konteks ini menjadi simplifikasi yang menempatkan orang miskin sebagai pelaku kriminal tanpa melihat sebab struktural yang melatarinya.
Media sosial menampilkan dinamika wacana yang lebih keras. Unggahan yang menyebut warga barbar atau biadab mendapat ribuan komentar. Ada pula konten yang menyamakan penjarahan dengan tindakan mencari kesempatan di saat orang lain susah. Pemberitaan seperti ini memunculkan polarisasi. Bahasa yang digunakan menyeret kasus penjarahan keluar dari konteks kemanusiaan menuju arena penghakiman moral. Padahal dalam teori wacana, bahasa penghakiman semacam ini berfungsi mempertahankan posisi dominan, yakni mereka yang tidak mengalami bencana dan merasa berhak menilai tindakan korban yang berusaha bertahan hidup.
Namun bukan berarti semua tindakan mengambil barang dapat dimaafkan. Ada pula video yang menunjukkan bahwa penjarahan terjadi tidak hanya pada barang kebutuhan pokok tetapi juga pada barang barang non esensial. Fenomena ini menunjukkan bahwa di tengah bencana, wacana kelangkaan dan ketakutan dapat membuat sebagian orang kehilangan kepekaan moral. Tetapi di sisi lain, bahasa yang digunakan dalam pemberitaan jarang membedakan antara tindakan survival dan tindakan oportunis. Semua digabung dalam satu istilah yang sama yaitu penjarahan. Akibatnya publik tidak mampu melihat gradasi perilaku dan tidak mampu membedakan tindakan yang lahir dari kebutuhan mendesak dengan tindakan yang lahir dari niat memanfaatkan kekacauan.
Pemberitaan Bulog juga menarik dianalisis. Dalam salah satu laporan, frasa massa menjarah gudang Bulog muncul berulang kali. Penggunaan frasa itu seolah menjelaskan bahwa semua warga yang datang ke lokasi adalah pelaku tindakan kriminal. Padahal dalam beberapa wawancara, warga menyatakan pintu gudang terbuka setelah diterjang banjir dan mereka hanya mengambil beras yang terapung dan diprediksi tidak bisa dikonsumsi lagi oleh Bulog. Frasa massa menjarah menyingkirkan kemungkinan bahwa kerusakan gudang adalah akibat banjir dan bukan akibat perusakan oleh warga. Pilihan bahasa semacam ini tidak hanya mengaburkan fakta tetapi juga membentuk stigma panjang terhadap warga setempat.
Dalam konteks wacana kritis, tindakan mengambil beras dari gudang Bulog sebenarnya dapat dilihat sebagai gejala dari kegagalan negara memenuhi kebutuhan dasar saat bencana. Ketika negara hadir dengan lambat, warga mengambil alih peran itu dengan cara yang kadang melanggar hukum. Namun bila bahasa yang dipakai media hanya menyoroti tindakan tanpa menampilkan kegagalan distribusi bantuan, maka publik kehilangan kesempatan untuk memahami akar masalah. Di sini kita melihat bagaimana bahasa tidak sekadar menjelaskan peristiwa tetapi juga mengarahkan kesadaran publik tentang siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang disalahkan.
Sayangnya media lebih memilih menampilkan visual dramatis ketimbang data yang lebih bermakna. Laporan BNPB terbaru menunjukkan bahwa akses jalan di sejumlah kecamatan masih tertutup lumpur dan jembatan penghubung putus. Lima ribu lebih warga masih berada di titik pengungsian tanpa pasokan makanan memadai. Bantuan logistik tertahan di pusat kota karena sungai meluap dan kendaraan tidak dapat melintas. Fakta fakta ini jarang mendapat ruang dalam pemberitaan yang lebih fokus pada aksi penjarahan. Akibatnya narasi publik berpindah dari soal penyelamatan korban menjadi soal kriminalisasi warga. Padahal selama bencana berlangsung, jaminan kebutuhan pangan adalah tanggung jawab negara dan kegagalan memenuhi kebutuhan dasar akan menciptakan tekanan sosial yang mudah meletup menjadi chaos.
Wacana digital menambah keruwetan. Banyak konten viral sengaja dibuat untuk menambah dramatisasi. Ada video editan yang menggambarkan penjarahan besar besaran padahal terjadi di lokasi berbeda. Ada pula narasi yang sengaja memancing amarah publik untuk menghasilkan klik. Dalam teori wacana, manipulasi semacam ini disebut sebagai produksi kepanikan moral, yakni situasi ketika media membesar besarkan perilaku tertentu sehingga publik percaya bahwa masalah itu lebih besar daripada kenyataan. Penjarahan dalam bencana menjadi komoditas naratif yang menguntungkan karena menimbulkan keterkejutan dan kemarahan yang mudah menyebar.
Opini publik yang terbentuk dari bahasa semacam itu pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Alih alih memperkuat solidaritas, wacana penjarahan justru membelah warga menjadi dua kelompok yaitu korban yang dipandang gelap mata dan warga yang menghakimi dari kejauhan. Padahal bencana membutuhkan bahasa yang merangkul dan memulihkan. Bahasa yang mampu memahami bahwa orang yang kelaparan tidak sedang menantang hukum tetapi sedang menghadapi krisis yang memaksa mereka melakukan hal hal yang mungkin tidak akan mereka lakukan dalam situasi normal.
Sudah saatnya kita mengubah cara kita membicarakan bencana. Kita perlu menyadari bahwa bahasa adalah alat yang menentukan posisi siapa yang bersalah dan siapa yang layak ditolong. Jika media memilih diksi yang lebih adil dan lebih kontekstual, publik dapat memahami bahwa penjarahan bukan hanya soal perilaku kriminal tetapi juga soal ketimpangan struktur sosial, lambannya distribusi bantuan, dan kegagalan pengelolaan risiko. Dengan demikian, kita tidak terjebak pada penghakiman moral semata tetapi juga melihat persoalan dengan kacamata kemanusiaan.
Bencana selalu membuka luka namun wacana yang keliru dapat memperlebar luka itu. Kasus penjarahan di Sumatra dan Aceh menunjukkan bahwa bahasa dapat membangun solidaritas tetapi juga dapat menghancurkannya. Tugas kitalah sebagai masyarakat berakal sehat untuk memastikan bahwa bahasa yang kita pilih tidak ikut menenggelamkan martabat korban dalam arus opini yang serba tergesa. Yang dibutuhkan korban bukan stigma tetapi bantuan dan kebijakan yang lebih cepat. Yang dibutuhkan publik bukan sensasi tetapi pemahaman yang lengkap.