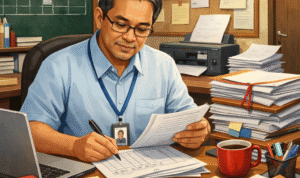Opini: Muh. Ikbal (Dosen Fakultas Bahasa dan Sastra UNM)
WARTAKATA.ID, MAKASSAR — Belakangan ini, di media sosial sering muncul satu kalimat yang terdengar sederhana, tetapi menyimpan kegelisahan kolektif: “Ada yang Bugis tapi tidak bisa bahasa Bugis?” Ia hadir dalam bentuk video singkat, candaan, sampai pengakuan jujur di kolom komentar—dan justru di situ letak seriusnya. Ketika identitas etnis dipertanyakan melalui kemampuan bertutur, bahasa tidak lagi sekadar alat komunikasi; ia berubah menjadi semacam “tanda keanggotaan” yang diam-diam memproduksi rasa malu, rasa kehilangan, dan kadang rasa bersalah.
Kegelisahan ini tidak lahir dari ruang hampa. Secara demografis, bahasa Bugis sesungguhnya termasuk bahasa besar. Data Sensus Penduduk 2010 mencatat penutur bahasa Bugis (usia 5 tahun ke atas) yang menggunakan bahasa itu sebagai bahasa sehari-hari di rumah mencapai 3.510.249 orang. Angka sebesar ini sering membuat kita merasa “aman”—seolah-olah bahasa Bugis tidak mungkin terancam.
Tetapi sosiolinguistik mengajarkan satu hal yang tajam: bahasa tidak melemah terutama karena jumlah etnisnya berkurang, melainkan karena pewarisan antargenerasi melemah. Dan pelemahan itu biasanya tidak bising; ia bekerja pelan di ruang keluarga, lalu meledak sebagai keresahan di ruang digital.
Di level nasional, Badan Bahasa (mengutip Long Form SP2020) menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga memang masih tinggi, tetapi turun pada generasi termuda: Generasi Z dan Generasi Alfa hanya menggunakan bahasa daerah di keluarga “di kisaran 61–62%”. Ini penting karena rumah adalah “pabrik penutur” paling menentukan.
Ketika rumah mulai menormalisasi bahasa lain sebagai default, anak tumbuh sebagai penutur pasif: paham, tetapi tidak menuturkan; mengerti, tetapi tidak percaya diri. Dalam banyak keluarga Bugis, situasinya terasa akrab: orang tua berbicara Bugis, anak menjawab Indonesia. Secara komunikasi percakapan tetap jalan, tetapi secara regenerasi penutur, bahasa sedang kehilangan masa depan.
Pemerintah lewat Kemendikbudristek pernah merumuskan masalahnya dengan sangat tegas: kepunahan bahasa terutama terjadi karena penutur “tidak lagi menggunakan dan/atau mewariskan” bahasa itu ke generasi berikutnya. Di sinilah “fenomena sosmed” menjadi semacam alarm sosial. Konten-konten yang mempertanyakan kemampuan berbahasa Bugis—atau mengaku tidak bisa—sebenarnya adalah bentuk metalinguistic awareness: masyarakat sedang menyadari ada yang retak dalam rantai pewarisan. Bahkan ada konten yang secara eksplisit memanggil kelompok itu, misalnya video bertanya “orang Bugis yang tidak bisa bahasa Bugis,” yang beredar dengan jejak atribusi ke TikTok.
Menariknya, media sosial tidak hanya menjadi tempat curhat, tetapi juga etalase perubahan praktik berbahasa. Ada penelitian yang menganalisis bagaimana unsur Bugis “muncul” dalam tuturan bahasa Indonesia penutur Bugis di TikTok—menunjukkan bahwa di ruang digital, yang terjadi sering bukan pemakaian Bugis secara penuh, melainkan jejak-jejak Bugis yang menempel pada Indonesia. Ini gejala yang sangat khas pada komunitas yang sedang bergeser: identitas linguistik tetap ada, tetapi diwujudkan lewat serpihan, bukan lewat kompetensi penuh.
Di luar Sulawesi Selatan, riset-riset tentang diaspora Bugis juga memperlihatkan pola yang konsisten: generasi muda Bugis yang lahir dan besar di wilayah multietnis cenderung beralih ke bahasa dominan setempat, sementara bahasa Bugis lebih kuat pada generasi tua. Studi tentang komunitas Bugis di Papua, misalnya, mencatat pergeseran ke Bahasa Indonesia dan Melayu Papua pada generasi muda. Bahkan ringkasan disertasi tentang anak keturunan Bugis di Jayapura menunjukkan sebagian besar informan anak mengaku tidak berbahasa Bugis di rumah.
Gambaran seperti ini membuat keresahan di Sulsel terasa makin masuk akal: jika di perantauan pergeseran berlangsung cepat karena tekanan lingkungan, di kampung halaman pun pergeseran bisa terjadi ketika “prestise” dan “kemudahan” bahasa Indonesia diam-diam menguasai ruang keluarga.
Karena itu, keresahan “keturunan Bugis tidak bisa menuturkan bahasa Bugis” sebetulnya adalah kritik sosial yang halus: kita sedang menyaksikan bahasa ibu bergeser dari alat hidup menjadi simbol budaya. Ia masih dipuji, tetapi tidak dipakai; masih dibanggakan, tetapi tidak diwariskan; masih dianggap identitas, tetapi tidak dianggap kebutuhan komunikasi harian. Dan saat simbol tidak lagi didukung praktik, yang lahir adalah generasi yang tetap merasa Bugis—namun tidak punya cukup perangkat bahasa untuk menuturkan kebugisannya secara utuh.
Jika media sosial hari ini dipenuhi pertanyaan-pertanyaan canggung tentang “kok saya tidak bisa bahasa Bugis?”, mungkin itu bukan bahan olok-olok, melainkan sinyal yang harus dibaca secara serius: ada generasi yang ingin kembali, tetapi tidak tahu pintu masuknya. Tugas komunitas—keluarga, sekolah, tokoh adat, dan juga kreator konten—bukan menertawakan ketidakfasihan, melainkan menciptakan ekologi tutur yang ramah bagi pemula. Sebab bahasa ibu tidak mati karena dibenci; ia mati karena lama-lama dianggap tidak perlu.