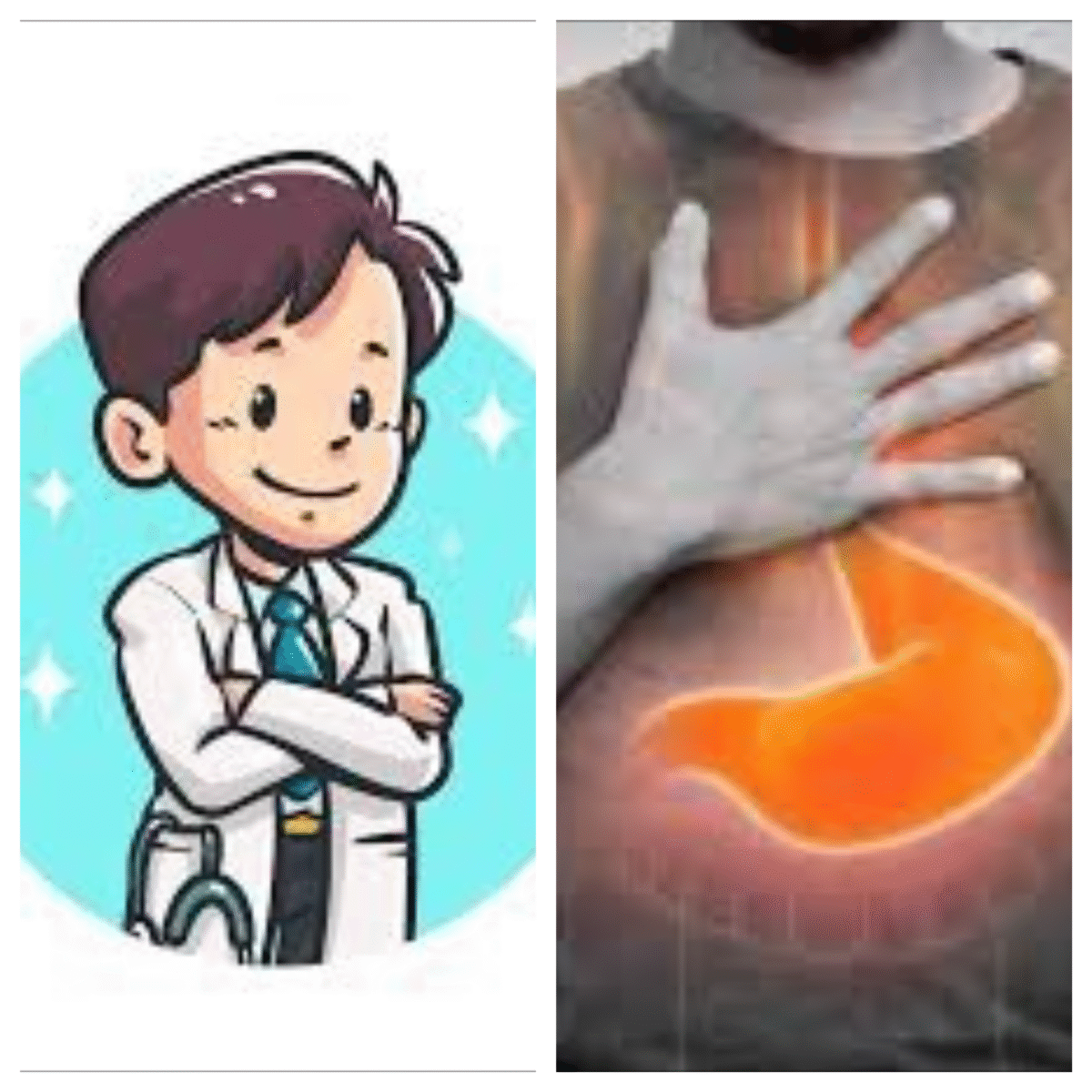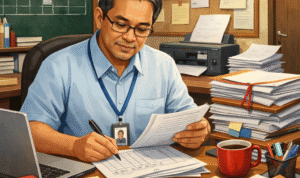Opini: Muh. Ikbal (Dosen Fakultas Bahasa dan Sastra UNM)
WARTAKATA.ID, MAKASSAR — Belakangan ini, ruang publik—terutama media sosial—ramai oleh perdebatan antara orang awam dan dokter. Salah satu isu yang sering memicu polemik adalah pernyataan medis bahwa GERD tidak menyebabkan serangan jantung. Ironisnya, penjelasan ilmiah yang disampaikan dokter justru kerap dibantah dengan penuh keyakinan oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang medis. Fenomena ini patut dibaca bukan semata sebagai persoalan kesehatan, melainkan sebagai persoalan bahasa dan cara manusia memandang pengetahuan.
Di ruang digital hari ini, opini personal sering kali diperlakukan setara—bahkan lebih dipercaya—daripada ilmu yang dibangun melalui pendidikan panjang, riset, dan pengalaman klinis. Bahasa ilmiah yang digunakan dokter memiliki ciri khas seperti hati-hati, berbasis data, dan menghindari klaim mutlak. Sebaliknya, bahasa orang awam sering bersandar pada pengalaman subjektif, misalnya rasa nyeri, sesak, cemas, dan ketakutan akan kematian. Masalah muncul ketika pengalaman pribadi dianggap cukup untuk membantah penjelasan akademis. Di titik inilah, pengalaman berubah menjadi klaim kebenaran.
Apakah ini bentuk kesombongan manusia? Sebagian iya. Ada yang bisa disebut kesombongan epistemik—perasaan bahwa pengetahuan yang diperoleh secara instan dari internet, potongan video, atau cerita orang lain dianggap setara dengan ilmu seorang dokter. Namun, tidak semuanya dapat disederhanakan sebagai kesombongan.
Lebih sering, penolakan terhadap dokter lahir dari ketidaktahuan yang bercampur kecemasan. Gejala GERD memang dapat menyerupai gejala serangan jantung. Bagi orang awam, rasa sakit di dada adalah bahasa tubuh yang menakutkan. Ketika bahasa medis mengatakan “tidak berbahaya”, sementara tubuh merasakan “seperti akan mati”, terjadi konflik makna. Dalam kondisi itu, sains kalah oleh rasa takut.
Masalahnya menjadi serius ketika ketidaktahuan itu berkembang menjadi sikap meremehkan otoritas ilmiah. Dokter tidak lagi diposisikan sebagai rujukan pengetahuan, melainkan hanya “satu suara di antara banyak komentar”. Jika semua pendapat dianggap sama nilainya, maka ilmu kehilangan wibawanya, dan masyarakat kehilangan arah.
Kita sedang menghadapi krisis literasi: bukan hanya literasi kesehatan, tetapi literasi bahasa dan pengetahuan. Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua pernyataan memiliki bobot yang sama, dan tidak semua pengalaman pribadi dapat dijadikan dasar generalisasi. Sementara itu, para akademisi dan dokter dituntut untuk terus menjembatani bahasa ilmiah agar lebih dipahami publik tanpa kehilangan ketepatan makna.
Menentang dokter soal GERD dan serangan jantung bukan sekadar soal beda pendapat. Ia adalah cermin zaman: ketika keberanian berbicara tidak selalu diiringi kesediaan belajar. Dan ketika bahasa asumsi mengalahkan bahasa ilmu, yang dipertaruhkan bukan hanya kebenaran, melainkan keselamatan manusia itu sendiri.