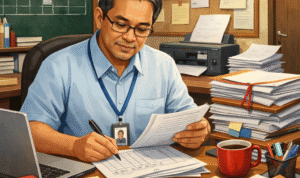Opini: Ir. Ar. Ivan Fachrul Marsa, S.T., M.Ars. IPM
Dosen Teknik Arsitektur FT UNM
WARTAKATA.ID, MAKASSAR — Banjir yang kian sering menyapa kota-kota besar bukanlah peristiwa alam semata. Ia adalah akumulasi dari keputusan manusia yang berulang kali mengabaikan keseimbangan ruang hidup. Perizinan bangunan yang longgar, minimnya daerah resapan air, dan menyusutnya ruang terbuka hijau telah mengubah kota menjadi hamparan beton yang rapuh menghadapi hujan. Dalam konteks ini, bencana sering kali bukan datang dari langit, melainkan lahir dari meja-meja kebijakan.
Perizinan bangunan seharusnya menjadi instrumen pengendali tata ruang, bukan sekadar administrasi pemenuhan izin investasi. Namun, dalam praktiknya, izin kerap diberikan tanpa pertimbangan daya dukung lingkungan. Bangunan menjulang di atas lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan, kawasan rawa, atau ruang hijau alami. Ketika fungsi ekologis ini hilang, air hujan tak lagi memiliki ruang untuk meresap. Kota pun berubah menjadi wadah limpasan.
Masalahnya diperparah oleh lemahnya pengawasan pasca-izin. Banyak bangunan yang melanggar koefisien dasar bangunan, menutup hampir seluruh permukaan lahan dengan beton atau paving. Drainase buatan dijadikan satu-satunya solusi, seolah-olah air hujan dapat “diperintah” untuk mengikuti saluran sempit yang sering tersumbat. Padahal, secara ekologis, air membutuhkan ruang, bukan sekadar saluran.
Daerah resapan air adalah infrastruktur alami yang sering diremehkan. Tanah terbuka, pepohonan, dan ruang hijau berfungsi sebagai sistem penyangga yang menyerap, menyaring, dan memperlambat aliran air. Ketika daerah ini dikorbankan atas nama pembangunan, kota kehilangan mekanisme alaminya untuk beradaptasi terhadap hujan ekstrem—fenomena yang kian sering terjadi akibat perubahan iklim.
Ruang Terbuka Hijau (RTH) seharusnya menjadi elemen wajib dalam perencanaan kota, bukan pelengkap estetika. RTH bukan sekadar taman kota untuk swafoto atau event seremonial, tetapi “paru-paru” dan “spons” ekologis yang menjaga siklus air dan kualitas udara. Ketika RTH terus menyusut dan tergantikan oleh bangunan komersial, kota kehilangan kemampuannya untuk bernapas dan menyerap risiko.
Yang lebih mengkhawatirkan, persoalan ini sering direproduksi melalui cara pandang pembangunan yang bias ekonomi. Pembangunan diukur dari jumlah bangunan, investasi, dan pertumbuhan fisik, bukan dari ketahanan lingkungan dan keberlanjutan hidup warga. Dalam logika seperti ini, alam selalu berada di posisi kompromi, sementara risiko ekologis diwariskan kepada masyarakat.
Sudah saatnya perizinan bangunan diletakkan dalam kerangka etika lingkungan. Setiap izin bukan hanya soal kepemilikan lahan, tetapi juga tanggung jawab ekologis. Pemerintah daerah perlu bertindak tegas dengan audit lingkungan, penguatan regulasi RTH minimal, serta sanksi nyata bagi pelanggaran tata ruang. Kota tidak boleh tumbuh dengan mengorbankan keselamatan warganya.
Banjir, genangan, dan krisis lingkungan perkotaan adalah alarm yang terus berbunyi. Jika perizinan bangunan tetap mengabaikan daerah resapan dan ruang terbuka hijau, maka kota sedang menggali masalahnya sendiri. Pembangunan sejati bukan soal seberapa padat kota dibangun, melainkan seberapa bijak ruang dikelola untuk keberlanjutan hidup bersama.