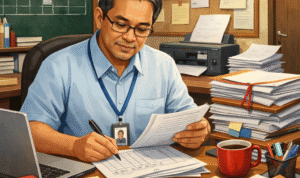Oleh: Dr. Agung Rinaldy Malik, M.Pd.
Dosen Fakultas Bahasa dan Sastra, UNM
Banjir informasi yang mengalir tanpa henti hari ini menempatkan kita pada situasi yang paradoks. Kita hidup pada masa ketika pengetahuan dapat diperoleh dengan sangat mudah, tetapi kemudahan itu tidak otomatis membuat manusia kian cerdas. Revolusi digital yang selama ini dipuji sebagai sumber percepatan, efisiensi, dan kebebasan berekspresi justru menyimpan ironi yang semakin tampak dalam praktik kehidupan intelektual. Teknologi membuat kita mampu menemukan jawaban dalam hitungan detik, namun di saat yang sama kemampuan untuk berpikir mendalam tampak melemah. Muncul pertanyaan yang tidak sederhana, apakah sesungguhnya kita sedang tumbuh menjadi lebih cerdas atau sekadar bergerak semakin cepat.
Perubahan cara manusia memproses informasi mulai terasa ketika teknologi berfungsi sebagai perpanjangan daya pikir. Mesin pencari menggantikan keperluan membaca secara utuh, ringkasan otomatis menggeser proses memahami dengan perlahan, dan kecerdasan buatan mampu menyusun esai dalam waktu singkat. Semua perkembangan ini mendorong lahirnya kebiasaan baru, yaitu kecenderungan mengandalkan jawaban instan. Keinginan untuk menemukan solusi paling cepat membuat proses merenung, menimbang, dan menguji gagasan semakin sering diabaikan. Padahal inti berpikir kritis terletak pada kemampuan mengambil jarak dari persoalan, membaca dengan saksama, dan memandang sesuatu dari berbagai sudut. Di tengah arus digital, banyak orang justru berhenti pada permukaan informasi.
Gejala tersebut tampak jelas dalam praktik menulis akademik. Banyak mahasiswa merasa lebih percaya diri mengerjakan tugas karena terbantu teknologi. Namun rasa percaya diri itu kerap menutupi kenyataan yang patut diwaspadai. Ketika teknologi dijadikan tumpuan utama, kemampuan menyusun argumen secara mandiri perlahan melemah. Perguruan tinggi kini menghadapi fenomena unik, tulisan mahasiswa terlihat semakin rapi dan tertata, tetapi satu dengan yang lain begitu mirip. Nada bahasa cenderung sama, alur penalaran seragam, bahkan daftar referensi pun sering berulang. Hal ini menandakan bahwa teknologi tidak hanya membantu menghasilkan teks, melainkan juga ikut membentuk cara berpikir penggunanya.
Pada saat yang sama, kebiasaan membaca turut mengalami pergeseran. Membaca tidak lagi dimaknai sebagai proses reflektif untuk menyerap dan mengolah gagasan. Aktivitas itu berubah menjadi upaya singkat menemukan jawaban yang dianggap paling relevan. Banyak mahasiswa hanya memindai paragraf untuk mencari kata kunci, bukan memahaminya secara menyeluruh. Mereka lebih sibuk menemukan bagian yang dianggap penting daripada memberi ruang bagi proses yang melahirkan pemahaman konseptual. Padahal kemampuan berpikir kritis hanya tumbuh ketika seseorang terbiasa membaca secara analitis dan berani mempertanyakan isi bacaan. Jika membaca dilakukan tergesa gesa, maka kemampuan kritis pun terpotong menjadi bagian bagian yang lepas.
Tentu teknologi menghadirkan manfaat yang tidak dapat disangkal. Kecerdasan buatan dapat membantu memperbaiki struktur tulisan, memeriksa kesalahan, bahkan menyarankan referensi tambahan. Namun manfaat ini sekaligus menjadi jebakan halus. Sebagian mahasiswa mulai lengah untuk berpikir karena merasa semua dapat diurus oleh sistem. Ketergantungan seperti ini berpotensi melahirkan kemalasan intelektual, yaitu keadaan ketika seseorang lebih mengandalkan kemampuan mesin dibandingkan daya pikir sendiri. Padahal menulis akademik sejatinya dimaksudkan untuk melatih kemampuan merumuskan gagasan, menguji argumen, dan mempertanggungjawabkannya. Kini proses tersebut kerap dilompati begitu saja.
Perubahan pola ini ikut menggeser cara kita memahami kecerdasan. Dahulu kecerdasan dinilai dari kedalaman analisis, kecermatan membaca data, dan kemampuan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Pada era digital, ukuran kecerdasan sering diringkas menjadi kemampuan merespons dengan cepat. Budaya kerja dan belajar makin akrab dengan penilaian berbasis kecepatan menyelesaikan tugas atau kelincahan menjawab pertanyaan. Padahal kecepatan tidak selalu sejalan dengan mutu pemikiran. Seseorang dapat sangat cepat, tetapi tetap dangkal. Produktivitas pun dapat meningkat tanpa diiringi pendalaman makna.
Dalam dunia akademik, keterampilan menulis tetap merupakan kemampuan yang tidak dapat digantikan mesin. Teknologi dapat menyarankan kalimat yang lebih efektif, tetapi tidak sanggup menggantikan pengalaman intelektual di balik tulisan. Karya tulis yang baik lahir dari pergulatan gagasan, hasil refleksi dari proses membaca, berdiskusi, dan mengaitkan teori dengan pengalaman. Tulisan yang sepenuhnya bersandar pada teknologi akan kehilangan napas kemanusiaan. Ia mungkin tampak rapi dan terstruktur, tetapi miskin kedalaman perspektif.
Meski demikian, teknologi tidak harus selalu diposisikan sebagai ancaman. Kecerdasan buatan dapat dipakai sebagai mitra yang memperkaya proses menulis. Ia dapat menjadi ruang uji coba gagasan, membantu menilai kekuatan logika, atau memperluas cakrawala referensi. Namun pengarah utama tetap harus manusia. Mahasiswa perlu menempatkan diri sebagai subjek yang menghasilkan gagasan, bukan sekadar pengguna yang menyalin saran sistem. Teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan penentu arah berpikir.
Fenomena ini juga terasa nyata di ruang publik. Media sosial yang bekerja dalam ritme cepat dan potongan potongan informasi mendorong masyarakat pada pola pikir reaktif. Banyak orang merespons isu tanpa memahami konteks dan sumber masalah. Opini publik yang terbentuk cenderung dangkal, emosional, dan mudah bergeser. Ketika ruang digital didominasi oleh respons spontan, kemampuan berpikir kritis masyarakat ikut tererosi. Kita menjadi lebih sering bereaksi daripada menganalisis.
Dalam situasi ini, dunia pendidikan terutama perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk memulihkan kualitas berpikir generasi muda. Pembelajaran perlu diarahkan kembali pada proses analitis, bukan sekadar pengumpulan jawaban yang dianggap benar. Dosen perlu merancang tugas yang menuntut mahasiswa menggali gagasan sendiri, menguji asumsi, dan mengembangkan argumen yang bertumpu pada data. Tugas menulis semestinya mensyaratkan membaca secara mendalam, berdiskusi, dan berefleksi, bukan hanya menghasilkan teks yang tampak rapi di permukaan.
Literasi digital juga perlu diajarkan dengan cara yang lebih utuh. Mahasiswa harus dibimbing untuk menilai keandalan sumber, mengenali bias, memahami etika penggunaan teknologi, dan menyadari bahwa pengetahuan tidak dihasilkan mesin semata. Mereka perlu memahami cara kerja algoritma, bagaimana informasi dipilihkan bagi pengguna, dan bagaimana proses itu membentuk pola pikir serta cara melihat dunia.
Dalam konteks penulisan akademik, ada tiga prinsip yang patut ditegaskan kembali. Prinsip keaslian mengingatkan bahwa gagasan penulis perlu lahir dari hasil pemaknaan pribadi yang jujur. Prinsip ketelitian menuntut argumen yang disusun dengan data yang kuat dan penalaran yang runtut. Prinsip kedalaman mendorong penulis melampaui permukaan informasi dan berupaya membangun analisis yang kaya. Ketiga prinsip ini tidak mungkin digantikan oleh teknologi, melainkan tumbuh dari latihan yang konsisten.
Revolusi digital membawa banyak keuntungan, namun juga mengajak kita menata ulang hubungan antara manusia dan teknologi. Kita tidak dapat terjebak pada anggapan bahwa kecepatan adalah bentuk baru kecerdasan. Kecerdasan justru berkaitan dengan kemampuan melihat persoalan secara mendalam dan menyusun pemahaman yang utuh. Kecepatan hanyalah fasilitas yang disediakan zaman.
Pertanyaan apakah kita menjadi lebih cerdas atau hanya lebih cepat tidak akan terjawab melalui slogan. Jawabannya tampak dalam cara kita menjalani keseharian. Cara kita membaca, cara kita menulis, cara kita berdiskusi, dan cara kita memanfaatkan teknologi akan menentukan apakah kita tumbuh sebagai pemikir atau sekadar pengguna. Revolusi digital seharusnya tidak menghapus kemampuan reflektif, melainkan memperkuat kesadaran untuk berpikir dengan lebih jernih. Era ini dapat melahirkan generasi dengan pemikiran tajam jika kita berani menjaga kedalaman di tengah percepatan. Teknologi dapat menjadi sahabat yang memperkaya gagasan selama kendali atas proses berpikir tetap berada di tangan manusia. Yang perlu kita jaga bukan hanya kecepatan merespons, tetapi kemampuan menafsirkan persoalan secara menyeluruh. Sebab pada akhirnya, kecerdasan bukan dinilai dari seberapa cepat kita menemukan jawaban, tetapi dari seberapa dalam kita memahami pertanyaan yang diajukan dunia kepada kita.