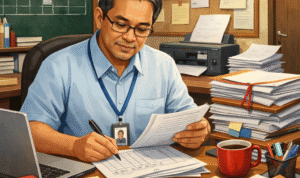Oleh: Dr. Agung Rinaldy Malik, M.Pd.
Dosen Fakultas Bahasa dan Sastra UNM
WARTAKATA.ID, MAKASSAR — Setiap 9 Desember, kata antikorupsi kembali lantang diucapkan. Ia hadir di spanduk, pidato resmi, unggahan media sosial, dan pernyataan lembaga negara. Namun, justru di tengah pengulangannya yang massif itu, kata antikorupsi terasa semakin hampa. Ia sering terdengar, tetapi semakin jarang dirasakan maknanya. Publik seolah terbiasa mendengar seruan moral tanpa perubahan nyata dalam praktik kekuasaan.
Dalam perspektif bahasa, kata bukan sekadar bunyi. Ia adalah pembawa makna, nilai, dan kepercayaan. Ketika sebuah kata terus diproduksi tanpa konsistensi tindakan, terjadilah apa yang bisa disebut sebagai erosi makna. Antikorupsi berubah dari komitmen etik menjadi slogan administratif. Ia diulang, tetapi tidak lagi diyakini. Di titik inilah bahasa kehilangan daya moralnya.
Kekosongan makna ini tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari jarak yang terlalu lebar antara bahasa resmi dan realitas sosial. Di satu sisi, kita mendengar pidato tentang integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Di sisi lain, publik terus disuguhi kabar korupsi yang melibatkan pejabat, penegak hukum, bahkan institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Ketika bahasa dan realitas tidak saling menguatkan, kepercayaan publik pun runtuh.
Sebagai dosen bahasa dan sastra, saya melihat korupsi bukan hanya sebagai persoalan hukum atau ekonomi, tetapi juga sebagai krisis bahasa publik. Bahasa yang seharusnya menjadi alat klarifikasi, justru berubah menjadi alat manipulasi. Kata-kata dipilih dengan hati-hati bukan untuk mengungkap kebenaran, melainkan untuk membungkusnya. Di ruang inilah eufemisme, jargon teknokratis, dan kalimat panjang yang kabur menjadi strategi kuasa.
Lebih jauh, korupsi juga hidup dalam kebiasaan berbahasa sehari-hari. Kita sering mendengar praktik curang dilembutkan dengan istilah “uang terima kasih”, “biaya koordinasi”, atau “sudah jadi kebiasaan”. Bahasa seperti ini bekerja pelan, tetapi efektif. Ia menormalisasi penyimpangan dan membuat korupsi tampak bukan sebagai kejahatan moral, melainkan sekadar urusan prosedural.
Hari Antikorupsi Sedunia seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan makna kata, bukan sekadar menambah suara. Antikorupsi harus kembali dihubungkan dengan tindakan yang konsisten, keberanian etik, dan keteladanan nyata. Tanpa itu, bahasa hanya menjadi gema kosong di ruang publik.
Perlawanan terhadap korupsi tidak cukup dimulai dari regulasi, tetapi juga dari kejujuran berbahasa. Kata yang jujur menuntut tindakan yang jujur. Jika tidak, antikorupsi akan terus hidup sebagai kata yang sering diucapkan, tetapi semakin kehilangan makna. Dan ketika bahasa kehilangan makna, yang runtuh bukan hanya kepercayaan, melainkan juga harapan bersama akan keadilan.