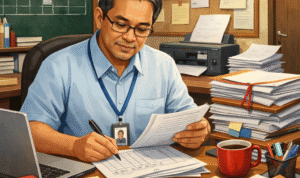Opini oleh: Muh. Ikbal (Dosen Fakultas Bahasa dan Sastra UNM)
WARTAKATA.ID, MAKASSAR — Setiap akhir tahun, publik kembali disuguhi pidato resmi para pemegang kekuasaan. Dalam berbagai bentuk—pidato presiden, pernyataan menteri, sambutan kepala daerah—bahasa tampil sebagai medium utama untuk menutup satu siklus waktu dan membuka harapan baru. Namun, pidato akhir tahun tidak pernah sekadar rangkaian kata penutup kalender. Ia adalah praktik diskursif yang sarat kepentingan, di mana bahasa bekerja bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk persepsi, mengelola emosi publik, dan mempertahankan legitimasi kekuasaan.
Dalam perspektif linguistik kritis, bahasa tidak pernah netral. Fairclough (1995) menegaskan bahwa bahasa selalu terikat pada relasi kuasa dan ideologi. Pidato akhir tahun menjadi ruang strategis bagi kekuasaan untuk mengontrol narasi: apa yang dianggap sebagai capaian, masalah, dan masa depan. Melalui pilihan diksi, struktur kalimat, serta penekanan tema tertentu, realitas sosial tidak sekadar dilaporkan, tetapi dikonstruksi.
Salah satu ciri paling menonjol dalam pidato akhir tahun adalah dominasi bahasa optimisme. Kata-kata seperti ke depan, komitmen, penguatan, perbaikan berkelanjutan, dan tantangan global berulang hampir tanpa variasi. Secara pragmatik, ungkapan-ungkapan ini berfungsi sebagai tindak tutur ilokusi—yakni tindakan berjanji, meyakinkan, dan menenangkan publik. Namun, persoalan muncul ketika tindak tutur tersebut tidak disertai efek perlokusi yang nyata, yakni perubahan konkret dalam kehidupan sosial. Janji tetap menjadi janji, sementara realitas struktural sering kali tidak bergeser.
Bahasa optimistik dalam pidato akhir tahun juga kerap berfungsi sebagai mekanisme pengaburan. Dalam analisis wacana kritis, strategi ini dikenal melalui penggunaan eufemisme dan nominalisasi. Masalah kompleks seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, atau krisis lingkungan sering dipresentasikan dalam bentuk istilah abstrak seperti tantangan, dinamika, atau agenda strategis. Dengan cara ini, aktor, sebab, dan tanggung jawab menjadi kabur. Bahasa tidak lagi membuka ruang evaluasi, tetapi justru menutupnya secara halus.
Lebih jauh, pidato akhir tahun memperlihatkan bagaimana kekuasaan mengelola waktu melalui bahasa. Masa lalu direduksi menjadi daftar capaian selektif, masa kini digambarkan sebagai fase transisi, sementara masa depan dipenuhi janji dan harapan. Struktur temporal ini penting secara ideologis. Dengan menekankan masa depan, kekuasaan mengalihkan perhatian publik dari kegagalan masa lalu dan persoalan yang belum terselesaikan. Bahasa masa depan bekerja sebagai alat penangguhan kritik.
Dalam kerangka teori tindak tutur Austin dan Searle, pidato akhir tahun sarat dengan ujaran performatif. Ketika pejabat menyatakan “kami berkomitmen” atau “pemerintah akan terus memperkuat,” ujaran tersebut bukan hanya deskriptif, tetapi performatif—ia menciptakan kesan tindakan. Namun, performativitas bahasa ini menjadi problematik ketika tidak diikuti mekanisme akuntabilitas. Kata-kata seolah telah “bekerja”, meski tindakan nyata belum terjadi.
Media turut memainkan peran penting dalam memperkuat kekuasaan kata. Kutipan pidato akhir tahun sering direproduksi sebagai judul berita tanpa konteks kritis. Bahasa resmi negara berpindah dari podium ke ruang redaksi, lalu ke layar gawai publik, dengan sedikit atau tanpa dekonstruksi. Akibatnya, bahasa kekuasaan menjadi wacana dominan yang diterima sebagai kebenaran, bukan sebagai konstruksi yang layak dipertanyakan.
Namun, di sinilah peran linguistik dan kajian bahasa menjadi krusial. Membaca pidato akhir tahun tidak cukup dilakukan secara permukaan. Diperlukan kesadaran kritis untuk menelisik apa yang dikatakan, apa yang tidak dikatakan, dan bagaimana sesuatu dikatakan. Bahasa yang tampak santun, optimis, dan menenangkan bisa saja menyimpan strategi ideologis yang kuat. Kritik linguistik tidak bertujuan menolak optimisme, melainkan memastikan bahwa optimisme tidak menjadi selubung bagi absennya tanggung jawab.
Pergantian tahun seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar perayaan retorika. Jika bahasa benar-benar ingin menjadi alat perubahan, maka pidato akhir tahun mesti bergerak dari bahasa janji menuju bahasa evaluasi. Dari slogan menuju keterbukaan data. Dari optimisme simbolik menuju keberanian mengakui keterbatasan. Tanpa itu, pidato akhir tahun hanya akan menjadi ritual linguistik yang berulang: kata-kata baru dalam kalender yang baru, tetapi dengan kuasa yang tetap bekerja dengan cara lama.
Pada akhirnya, kekuasaan kata hanya akan bermakna jika disertai etika berbahasa. Bahasa yang bertanggung jawab bukan bahasa yang paling indah terdengar, melainkan bahasa yang membuka ruang dialog, kritik, dan perubahan nyata. Tahun boleh berganti, tetapi kesadaran linguistik publik tidak boleh berhenti pada tepuk tangan atas pidato. Ia harus berlanjut pada pertanyaan: kata-kata ini bekerja untuk siapa, dan sejauh mana ia mengubah realitas kita bersama.