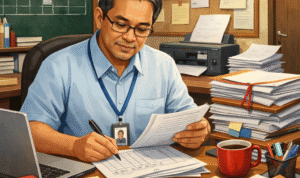Oleh: Muh. Ikbal (Dosen Fakultas Bahasa dan Sastra UNM)
WARTAKATA.ID, MAKASSAR — Dalam sepekan terakhir, wacana beasiswa LPDP kembali ramai karena arahan agar alokasinya lebih banyak diarahkan ke bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Reaksi publik pun cepat terbelah: sebagian menyambut karena Indonesia memang butuh lompatan iptek, sebagian lain khawatir ilmu sosial-humaniora (Soshum) akan terdorong ke pinggir sebagai pelengkap. Persoalannya sebenarnya bukan memilih salah satu, melainkan bagaimana negara mendesain prioritas tanpa menciptakan hierarki ilmu yang pada akhirnya justru mengganggu tujuan pembangunan itu sendiri.
Argumen pemerintah mudah dimengerti: mengejar ketertinggalan iptek dan menyiapkan talenta untuk kebutuhan strategis nasional. Jika yang dikejar adalah daya saing dan kemandirian industri, logika STEM memang tampak paling cepat. Lebih banyak insinyur, peneliti material, ahli data, tenaga kesehatan, dan inovator teknologi. Dengan stok talenta seperti itu, mesin ekonomi terlihat bisa bergerak lebih kencang, dan ketergantungan pada teknologi luar negeri diharapkan menurun.
Masalahnya, teknologi tidak hidup di ruang hampa. Ia selalu bekerja di dalam masyarakat: ada aturan, budaya, etika, ketimpangan akses, politik anggaran, konflik kepentingan, perilaku organisasi, dan penerimaan publik. Bayangkan Indonesia sukses “mencetak” ribuan talenta AI, tetapi regulasi perlindungan data masih lemah, birokrasi pengadaan tidak adaptif, literasi publik rendah sehingga inovasi mudah ditolak atau disalahgunakan, tata kelola riset-kampus tidak terkonsolidasi, dan dampak sosialnya—mulai bias algoritma, disinformasi, polarisasi, sampai tekanan di pasar kerja—tidak dimitigasi. Pada kondisi seperti itu, problemnya bukan semata kekurangan STEM, melainkan kekurangan Soshum yang kuat sebagai kemudi: perancang kebijakan, ahli hukum-teknologi, analis kebijakan publik, ekonom kelembagaan, peneliti pendidikan, ilmuwan komunikasi, hingga sosiolog inovasi.
Risiko terbesar: Soshum dipaksa jadi ornamen, padahal ia infrastruktur sosial
Jika prioritas STEM diterjemahkan secara kaku menjadi “Soshum cukup sisa”, ada risiko kebijakan publik menjadi miskin konteks. Banyak program yang secara teknis masuk akal, tetapi runtuh ketika berhadapan dengan realitas sosial: resistensi warga, ketidakpercayaan, ketimpangan akses, konflik lahan, atau insentif yang didesain keliru. Risiko berikutnya, inovasi teknologi justru tidak terserap karena ekosistemnya tidak siap. Teknologi butuh regulasi, model bisnis, manajemen perubahan organisasi, komunikasi risiko, serta desain layanan publik yang berpihak pada pengguna—dan banyak aspek itu berada di wilayah Soshum yang “keras”, bukan sekadar wacana. Risiko lain yang tak kalah serius adalah melemahnya keadilan sosial. Tanpa riset sosial yang kuat, teknologi mudah memperlebar jurang kota–desa, kaya–miskin, pusat–daerah. Pembangunan tampak maju di statistik, tetapi rapuh pada kohesi sosial dan rasa keadilan.
Jalan tengah: STEM + Soshum sebagai satu paket kebijakan
Jika pemerintah ingin memprioritaskan STEM untuk mengejar ketertinggalan iptek, itu bisa masuk akal—dengan desain yang presisi dan adil. Negara perlu menegaskan bahwa Soshum yang strategis bukan “sisa kuota”, melainkan bagian inti ekosistem pembangunan. Alih-alih menggeneralisasi Soshum, pemerintah bisa memetakan klaster yang langsung menopang agenda industri dan layanan publik: kebijakan publik, hukum-teknologi, ekonomi industri, pendidikan, komunikasi sains, tata kelola data, studi keamanan, hingga antropologi desain layanan. Selain itu, pendekatan interdisipliner perlu dijadikan standar, bukan bonus. Banyak problem nasional memerlukan irisan “teknologi × manusia”: AI untuk layanan publik harus bicara governance dan etika; ketahanan pangan harus bicara perilaku pelaku usaha, rantai nilai, serta desain insentif; energi dan hilirisasi butuh analisis kelembagaan, komunikasi risiko, dan skema keadilan transisi. Jika orientasinya benar-benar dampak, maka yang diukur seharusnya kontribusi pascastudi: output riset, adopsi inovasi, perbaikan layanan, dan kebijakan yang lebih efektif—bukan sekadar label jurusan STEM atau Soshum.
Mengutamakan STEM dalam LPDP bisa menjadi langkah berani, bahkan perlu, jika tujuannya mengejar ketertinggalan iptek. Namun negara akan rugi besar bila Soshum diperlakukan sebagai anak tiri, sebab pembangunan tidak hanya membutuhkan mesin, melainkan juga kemudi—agar laju teknologi tidak menabrak realitas sosial. Formula yang lebih sehat bukan “STEM menang, Soshum kalah”, melainkan STEM dipercepat, Soshum diperkokoh, lalu keduanya dikawinkan dalam desain kebijakan berbasis dampak. Di situlah LPDP menjadi investasi peradaban, bukan sekadar lomba jurusan.